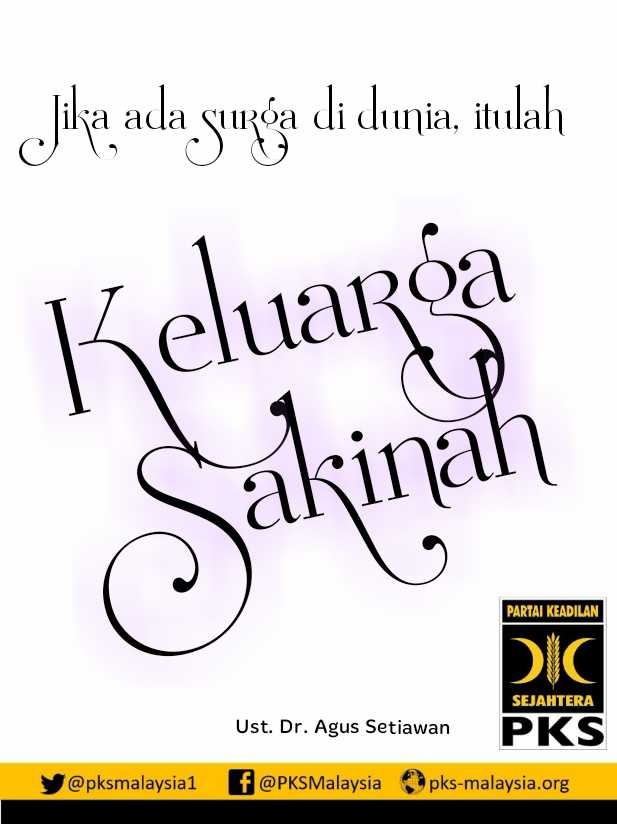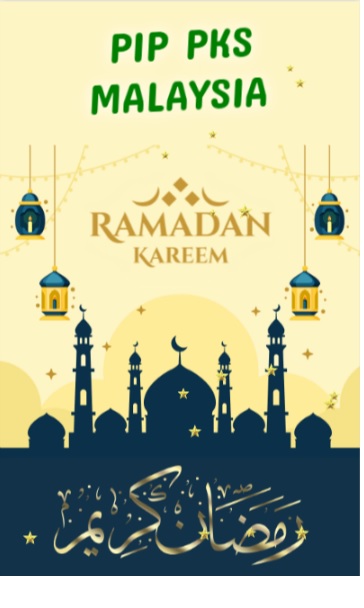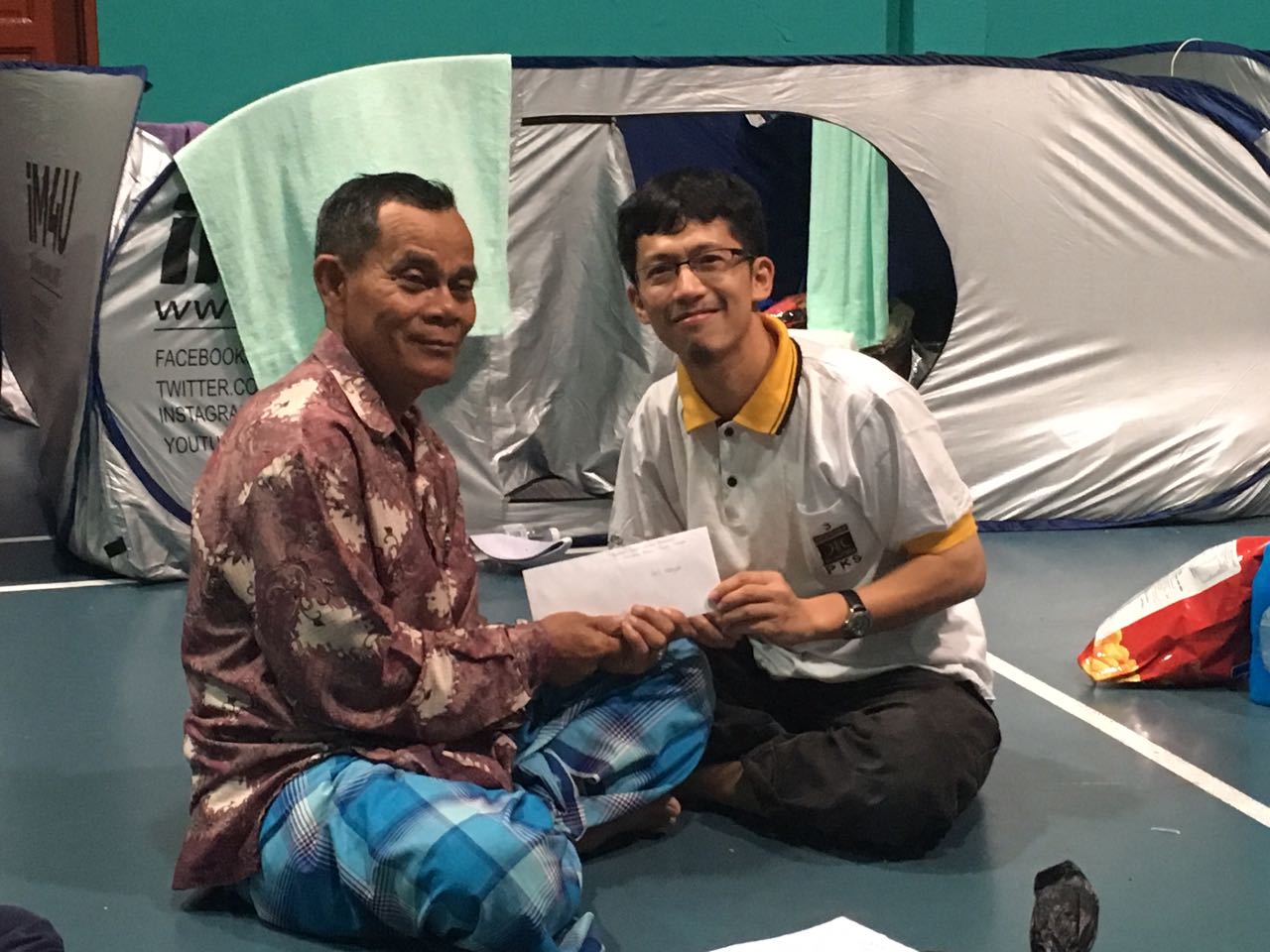Oleh: Ustadz Dr. Muntaha. A., Lc.
Di sudut lain ada juga ulama’ tabi’in yang menggunakan qiyas, misalnya ‘Ikrimah (w. 105 H/723 M), murid Ibnu Abbas yang juga ulama besar Makkah ini ketika disampaikan kepada beliau hadits Ummu Salamah, beliau mengakatan: “Tidaklah sebaiknya orang itu meninggalkan berhubungan badan dan wewangian”. Maksudnya, jika memotong kuku dan rambut dilarang tentu berhubungan badan harus dilarang juga, sebab lebih berat. Qiyas ini diperkuat lagi oleh Ibnu ‘Abdil Barr (w. 463H/1071 M), tokoh penting madhab Maliki, beliau berkata: “Semua ulama’ telah _ijma’_ (konsensus), bahwa berhubungan badan di sepuluh awal Dzul Hijjah bagi yang ingin berqurban diperbolehkan, maka yang kurang dari itu hukumnya mubah”. Logika Ibnu Abdil Barr juga sangat relevan, dari sekian banyak pantangan ihram, berhubungan badan tidak sebanding dengan memotong rambut dan kuku. Boleh jadi ada yang menyanggah dengan kaidah ‘tidak boleh dalam ibadah’, sanggahan seperti wajar, namun kaidah tersebut terlalu umum dan perlu perincian mendalam, dan realitanya sangat banyak praktek qiyas dalam ibadah dalam kitab-kitab fiqih.
Adapun yang berpendapat bahwa larangan tetap berlaku dengan mendasarkan kepada hadits Ummu Salamah, alasan yang mendasarinya sebagai berikut:
Hadits dari Aisyah sangat umum sedangkan hadits Ummu Salamah untuk peristiwa yang khusus, sesuai dengan kaidah, yang khusus harus didahulukan dari pada yang umum.
Hadits ‘Aisyah menerangkan perbuatan Nabi saw, sedangkan hadits Ummu Salamah menyebutkan sabda Nabi saw, dan dalam istinbath hukum dari hadits, ucapan Nabi saw lebih didahulukan daripada perbuatannya, sebab boleh jadi perbuatannya hanya khusus untuk beliau. Dengan demikian hadits Ummu Salamah lebih berhak untuk diambil.
Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M) yang berpendapat haramnya mencukur rambut dan memotong kuku membedakan hukum bagi orang yang berqurban dengan mengirimkan ke Makkah dan tetap tinggal di rumahnya dan orang yang berniat ingin menyembelih. Meskipun alasan ini sudah terjawab dengan komentar Imam as-Syafi’i di atas.
Dari metode istinbath yang berbeda-beda ini maka kesimpulan hukumnya juga berbeda, inilah yang disebut ijtihad ulama’ dalam memutuskan hukum, meskipun sudah ada nash yang shahih, ijtihad dalam persoalan ini tetap diperlukan sebab meskipun ada nash agama, namun katagorinya bukan yang qath’i, sehingga maksud dari isi kandungannya masih multi tafsir.
Oleh karenanya para ulama’ berbeda dalam memutuskan hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin berqurban jika hilal bulan Dzul Hijjah sudah terlihat, minimal ada empat pendapat:
1. Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) dan jumhur Hanafiyyah: Hukumnya boleh, tidak makruh dan tidak ada masalah apapun.
2. Pengikut Abu Hanifah yang muta’akkhirin: Tidak apa-apa, tidak makruh namun khilaful aula (meninggalkan yang mustahabb).
3. Al-Malikiyyah dan As-Syafi’iyyah: Disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku bagi yang hendak berqurban dan jika memotongnya termasuk makruh tanzih, namun bukan haram.
4. Imam Ahmad, Dawud ad-Dzahiri (w. 270 H/883 M) dan beberapa ulama lain menyatakan hukumnya haram jika memotong rambut dan kuku.
Dari paparan di atas, dari ulama’ madzhab hanya Imam Ahmad yang bersikukuh hukumnya haram, adapun jumhur ulama’ madzhab lebih cenderung memutuskan hukumnya adalah makruh, bahkan makruh karahah tanzih, yang berarti seyogyanya tidak dilakukan.
Pelajaran penting dari hadits ini
Terlepas dari pilihan-pilihan hukum yang sudah matang dan dikaji dengan mendalam oleh para ulama’ hadits dan juga fuqaha’ dan diskusinya sudah dibahas tuntas di dalam kitab-kitab fiqih dan syarah-syarah hadits, ada pelajaran penting dari hadits ini:
1. Memahami teks agama tanpa bimbingan ulama’ adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Belajar sendiri dari nash-nash al-Qur’an dan hadits tanpa merujuk ke tafsir dan syarah-syarah hadits adalah tindakan yang sangat gegabah, dan dikhawatirkan akan mendapatkan kesimpulan yang salah.
2. Nash al-Qur’an dan nash hadits Nabi yang berupa lafadz larangan, meskipun dgn redaksi yang keras, belum tentu kesimpulan hukumnya adalah haram. Sebab kata larangan memiliki indikasi makna yang bermacam-macam, untuk mengetahui hal ini, seseorang perlu mempelajari materi dilalatul alfadz yang dibahas di dalam disiplin ilmu ushul fiqih.
3. Tidak semua nash dalam al-Qur’an dan hadits mengandung maksud qath’i (hukumnya pasti, tidak menerima perbedaan), namun kebanyakan nash adalah dhanni (relatif).
4. Suatu hadits, meskipun katagorinya shahih, bukan berarti dengan serta merta bisa diambil dzahirnya dan diamalkan, perlu ditinjau terlebih dahulu, boleh jadi ada hadits yang lain di dalam kasus yang sama, bisa jadi ada naskh (pembatalan hukum), dan lain sebagainya.
5. Para salafusshalih, dalam hal ini para sahabat dan tabi’in juga terbiasa berbeda dalam masalah ijtihadiyyah. Hal ini bisa dilihat dari sikap para tabi’in yang melaporkan persoalannya kepada Aisyah ra juga sikap para ulama’ tabi’in dalam menyikapi hadits Ummu Salamah ra.
6. Pilihan hukum tertentu dari masalah-masalah khilafiyyah tidak boleh mengganggu muslim yang lain yang berbeda pilihan. Bahkan tidak diperlukan _nahi munkar_ dalam persoalan seperti ini. Sebab semuanya berdasarkan dalil yang sama-sama dianggap kuat.
7. Hadits ini hanya satu dari beratus-ratus hukum yang di dalamnya terjadi khilaf di kalangan ulama’, sehingga semakin luas wacana berpikir seseorang dalam dalil-dalil agama, maka akan semakin berlapang dada dalam menyikapi persoalan umat.
8. Merasa paling di atas sunnah hanya dengan berpihak pada satu pilihan hukum yang dhanni tanpa toleransi akan memicu perselisihan di antara umat Islam.
9. Ilmu agama demikian luas, dalil agama juga demikian banyak, akan sangat berbahaya jika hanya berpegang kepada satu dan dua dalil dan tidak mau mencari yang lain dan menutup hati dari kaluasan ilmu yang tak berbatas.
10. Terkadang seseorang sudah merasa paling benar dalam pilihan hukum di satu masa, namun lambat laun seiring dengan berkembangnya wawasan keagamaan, maka dada juga akan semakin luas untuk menerima perbedaan yang dalam ranah khilafiyyah yang mu’tabar.
11. Masalah ijtihadiyyah seperti di atas bukanlah tolok ukur al-haqq dan al-bathil, namun ranahnya adalah al-shawab (benar) dan al-khatha’ (tersalah), yang berijtihad dan benar akan mendapat dua pahala dan yang berijtihad dan tersalah tetap mendapatkan satu pahala.
Wallahu a’lam.